
Ludwig Wittgenstein: Filsuf yang Tidak Ingin Menjadi Filsuf10 min read
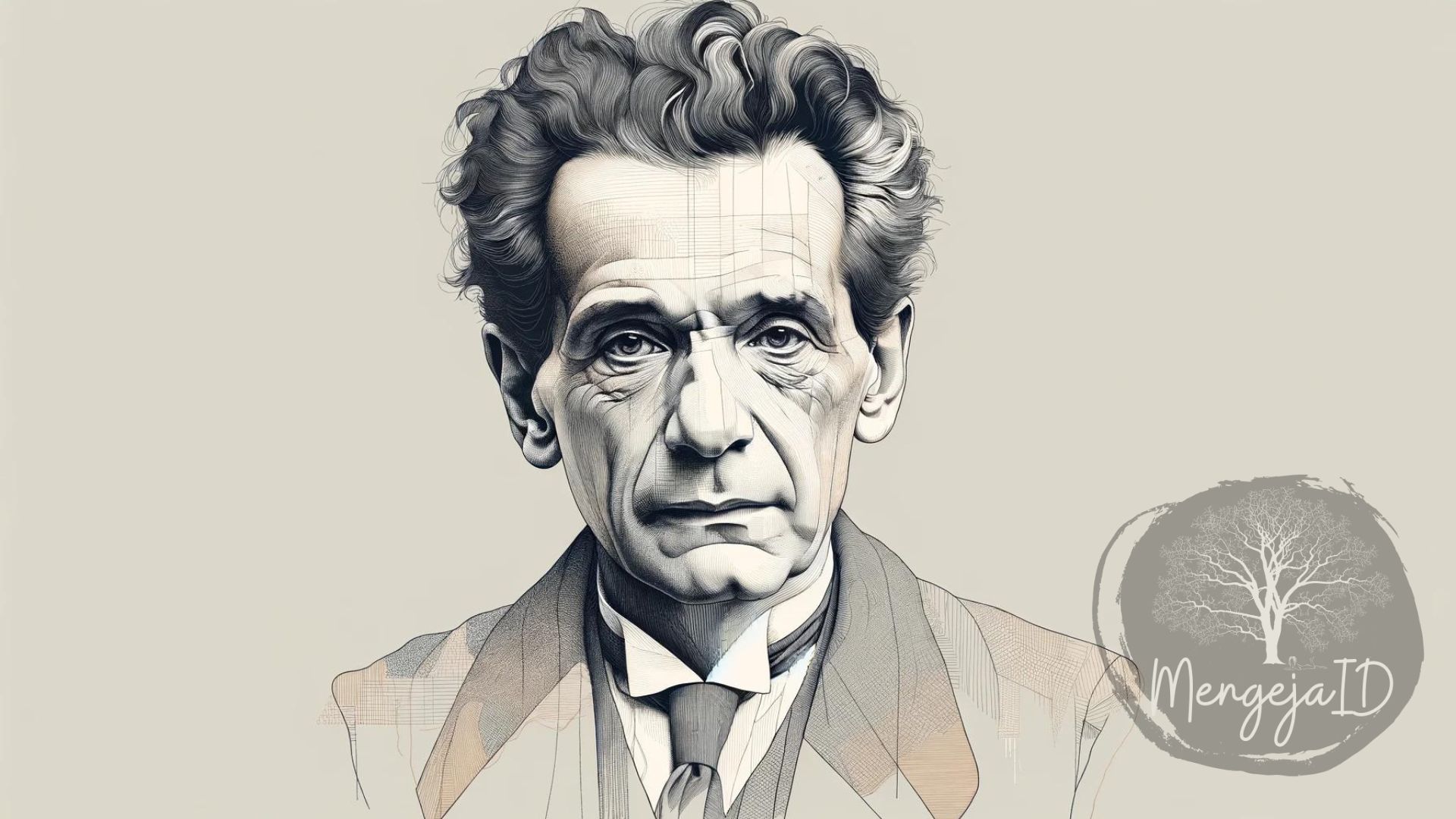
Ludwig Wittgenstein, yang berasal dari Wina, adalah salah satu pemikir yang paling berpengaruh dan kompleks di abad ke-20. Dia tidak hanya seorang filsuf, tetapi juga seseorang yang mengalami berbagai fase dalam karier akademiknya, serta perjuangan dalam Perang Dunia Pertama. Lebih menarik lagi, Wittgenstein mengalami perubahan radikal dalam pandangan filsafatnya di pertengahan kehidupannya, suatu peristiwa yang menandai transisi dari apa yang sering disebut sebagai fase “Wittgenstein Awal” ke “Wittgenstein Akhir”.
Sebagai tokoh pemikiran, Wittgenstein memegang keyakinan yang amat berani: dia percaya bahwa dia telah berhasil menyelesaikan semua masalah filsafat, dan ia merasa bahwa ini terjadi tidak hanya satu kali, melainkan dua kali sepanjang hidupnya. Ini mencerminkan tidak hanya kecerdasan dan kedalaman pemikirannya, tetapi juga keberanian intelektualnya untuk terus menilai ulang dan mengembangkan pemikiran-pemikirannya.
Artikel ini akan mengeksplorasi lebih dalam tentang kehidupan pribadi Wittgenstein, konteks sosial dan budaya di mana dia hidup, serta transisi signifikan yang dia alami dari fase awal ke fase akhir kariernya sebagai filsuf. Dengan memahami latar belakang ini, pembaca akan mendapatkan wawasan yang lebih luas tentang bagaimana dan mengapa Wittgenstein datang pada kesimpulan filsafatnya yang radikal, serta implikasi pemikirannya bagi dunia filsafat modern.
Filsuf yang Ambivalen
Ludwig Wittgenstein dilahirkan pada tahun 1889 dalam sebuah keluarga yang merupakan salah satu yang terkaya di Eropa saat itu. Sebagai anak bungsu dari sembilan bersaudara, Ludwig dibesarkan di Palais Wittgenstein di Wina, sebuah bangunan megah yang kini tidak lagi berdiri, meskipun masih tersisa beberapa gambar eksterior dan interior yang memberikan gambaran tentang keindahannya. Ayahnya, Karl Wittgenstein, adalah seorang figur penting dalam industri baja dan dikenal sebagai pelindung seni yang besar. Dalam upayanya untuk menciptakan warisan melalui kelima anak laki-lakinya, tragisnya, tiga di antaranya memilih untuk mengakhiri hidup mereka sendiri.

Rumah keluarga Wittgenstein sering dipenuhi dengan karya seni, patung, dan bahkan seniman-seniman itu sendiri, menciptakan lingkungan yang kaya dengan pengaruh kreatif dan intelektual. Saudari Ludwig, Margaret, bahkan diabadikan dalam sebuah lukisan oleh Gustav Klimt. Meskipun berada dalam kelimpahan materi, Ludwig sendiri memilih jalan yang berbeda; setelah kematian ayahnya, dia menolak bagian warisan dan memilih untuk hidup dengan cara yang lebih sederhana dan terkadang keras.
Dalam masa mudanya, Ludwig sangat tertarik pada rekayasa dan melanjutkan pendidikan di bidang aeronautika, yang kemudian memicu minatnya pada filsafat matematika dan logika. Penemuan ini membawanya untuk menghubungi Gottlob Frege, seorang logikawan terkenal. Impresi Frege atas ketajaman Wittgenstein menyebabkan dia direkomendasikan untuk belajar dengan Bertrand Russell, seorang mentor yang akan sangat mempengaruhi pemikiran Wittgenstein.
Ketertarikannya dalam filsafat membuahkan karya pertama yang berpengaruh, Tractatus Logico-Philosophicus. Namun, Perang Dunia I mengganggu pekerjaannya, memaksa Wittgenstein untuk mendaftar dan bertugas selama empat tahun. Cuti militernya merupakan masa sulit; beberapa kehilangan pribadi termasuk kematian anggota keluarga dan teman dekat, serta penolakan penerbit untuk menerbitkan bukunya, semakin menambah beban emosionalnya. Setelah kembali ke dinas, dia ditangkap oleh Sekutu dan menghabiskan sembilan bulan dalam tawanan perang. Ini adalah periode gelap dalam hidupnya, namun juga merupakan saat yang membentuk kegigihannya dan kedalaman pemikiran filsafatnya.
Filsuf yang Tidak Ingin Menjadi Filsuf
Tahun-tahun pasca Perang Dunia Pertama menjadi masa yang sangat kritis bagi Ludwig Wittgenstein, yang menyebabkan dia menjauh dari dunia filsafat untuk sementara waktu. Setelah perang, Wittgenstein yang terguncang secara emosional memutuskan untuk mengejar kehidupan yang lebih sederhana sebagai guru sekolah dasar di desa-desa terpencil di Austria. Namun, upayanya ini tidak berjalan mulus. Kepribadiannya yang halus dan eksentrik tidak cocok dengan lingkungan kota kecil, dan pendekatannya yang keras terhadap disiplin—termasuk penerapan hukuman fisik—menyebabkan ketidaknyamanan dan konflik. Setelah beberapa kali berpindah posisi mengajar dan insiden di mana seorang anak pingsan akibat hukuman fisik darinya, Wittgenstein menghadapi persidangan dan akhirnya meninggalkan dunia pendidikan.

Dalam periode ini, Wittgenstein juga terlibat dalam proyek arsitektur yang didesain untuk saudara perempuannya, Margaret. Proyek ini menghasilkan Haus Wittgenstein, sebuah bangunan yang kini menjadi salah satu situs bersejarah yang dapat dikunjungi di Wina.
Sementara itu, mentor lama Wittgenstein, Bertrand Russell, menggunakan pengaruhnya untuk memastikan Tractatus Logico-Philosophicus, karya Wittgenstein, diterbitkan. Penerbitan buku ini memicu pembentukan Lingkaran Wina, kelompok akademisi yang secara intensif membahas ide-ide yang diungkapkan dalam Tractatus. Kelompok ini menginspirasi gerakan filsafat baru, yaitu positivisme logis. Meskipun sering terlibat dalam diskusi dengan Lingkaran Wina, Wittgenstein merasa bahwa ide-idenya seringkali disalahpahami dan ini menyebabkan perasaan bermusuhan dengan beberapa anggotanya.
Kembalinya Wittgenstein ke dunia filsafat terjadi ketika dia menerima posisi dosen di Trinity College, Cambridge pada tahun 1929. Selama bertahun-tahun di sana, dia mengembangkan apa yang kemudian dikenal sebagai “Wittgenstein Akhir”, yang menentang banyak dari prinsip-prinsip yang sebelumnya ia pegang. Dia tetap mengajar hingga hampir dua dekade sebelum akhirnya mengundurkan diri untuk fokus pada pekerjaannya sendiri. Wittgenstein meninggal pada tahun 1951, tanpa melihat banyak dari karya-karyanya diterbitkan selama hidupnya. Namun, banyak dari tulisannya yang sangat berpengaruh, termasuk buku Philosophical Investigations, diterbitkan secara pasca kematian berkat bantuan dari murid-muridnya yang setia.
Melalui fase-fase yang berbeda dalam hidup dan kariernya, Ludwig Wittgenstein terus mempengaruhi dan menginspirasi dunia filsafat, menandai dirinya sebagai salah satu pemikir terbesar di abad ke-20.
Wittgenstein “Awal”
Filsafat Ludwig Wittgenstein memang unik karena memiliki dua periode yang sangat berbeda, yang membuat banyak akademisi memandangnya sebagai dua filsuf yang berbeda dalam satu sosok: Wittgenstein “Awal” dan Wittgenstein “Akhir”. Periode awal Wittgenstein ditandai dengan penulisannya atas Tractatus Logico-Philosophicus, sebuah karya yang sangat berpengaruh dan menjadi titik tolak pembentukan Lingkaran Wina, sebuah kelompok filsuf yang mengadopsi dan mengembangkan beberapa ide-idenya.

Tractatus, yang ditulis oleh Wittgenstein setelah pengalaman intensnya di Perang Dunia I, berfokus pada relasi antara bahasa, logika, dan dunia. Di era tersebut, minat terhadap logika sedang berkembang, dipicu oleh karya-karya inovatif seperti logika predikat aksiomatik yang diciptakan oleh Gottlob Frege. Filsuf-filsuf menyadari pentingnya hasil kerja Frege dalam memberikan fondasi yang lebih formal dan sistematis untuk logika.
Dalam Tractatus, Wittgenstein mencoba mendemonstrasikan bagaimana logika, bahasa, dan realitas saling terkait. Dia melihat logika sebagai esensi dari bahasa, sebuah alat untuk membedah dan memahami struktur dasar dari pikiran kita dan cara kita menyampaikan makna. Wittgenstein mengajukan bahwa tujuan utama bahasa adalah untuk mengklarifikasi apa yang bisa diucapkan dan dipikirkan dengan bermakna, menyingkirkan apa yang dia anggap sebagai kekeliruan-kekeliruan konseptual dalam filsafat dan logika.
Salah satu konsep sentral yang dia kembangkan adalah teori gambaran bahasa. Menurut pandangan ini, bahasa dan pikiran adalah isomorfis, atau memiliki struktur yang sama dengan realitas yang mereka representasikan. Wittgenstein menggunakan analogi model pesawat yang mewakili pesawat nyata untuk menjelaskan ide ini. Sama seperti model yang bisa merepresentasikan objek nyata dengan menunjukkan beberapa properti yang sama (seperti rasio dimensi dan warna), demikian pula bahasa merepresentasikan realitas dengan mengikuti struktur logis yang sama.
Ide-ide ini sangat berdampak pada cara filsuf memandang bahasa dan logika, dan memainkan peran penting dalam pengembangan filosofi analitik di abad ke-20. Namun, seiring waktu, Wittgenstein sendiri menjadi kritis terhadap beberapa aspek dari pandangan awalnya ini, yang memimpin ke fase berikutnya dalam pemikirannya, yang sering disebut sebagai periode “Wittgenstein Akhir”.
Ketidakbermaknaan Filsafat
Dalam Tractatus Logico-Philosophicus, Ludwig Wittgenstein mengeksplorasi batasan-batasan bahasa dan apa yang dapat diungkapkan secara bermakna melalui kata-kata. Inti dari pemikiran Wittgenstein adalah usahanya untuk memisahkan apa yang dapat diungkapkan dengan jelas dan apa yang berada di luar kemampuan bahasa. Dia berargumen bahwa banyak diskusi dalam filsafat—seperti pertanyaan tentang esensi keadilan atau makna hidup—sebenarnya tidak mengarah pada pemahaman yang lebih dalam atau kebenaran, karena mereka tidak didukung oleh fakta-fakta empiris yang dapat diverifikasi. Menurut Wittgenstein, pertanyaan seperti ini tidak memiliki jawaban konkret karena tidak ada “fakta” dalam realitas yang dapat menjawabnya. Oleh karena itu, debat semacam ini sering kali berujung pada kebingungan linguistik bukan pada kebenaran filosofis yang substansial.
Salah satu konsep terkenal dari Tractatus adalah ide bahwa seseorang harus “membuang tangga setelah ia memanjatnya.” Ini menggambarkan Wittgenstein yang menyatakan bahwa setelah seseorang memahami batasan-batasan yang diajukan oleh buku tersebut terhadap apa yang dapat diungkapkan secara logis, mereka harus meninggalkan atau melampaui proposisi-proposisi tersebut. Ini merupakan refleksi dari sikap Wittgenstein sendiri bahwa proposisi yang dia tawarkan dalam Tractatus—meskipun mengandung pemahaman yang mendalam tentang logika dan bahasa—akhirnya harus ditinggalkan karena mereka mencapai batas-batas kegunaannya dalam memahami dunia.
Hal ini menciptakan sebuah paradoks interpretatif: bagaimana seseorang bisa mendapatkan nilai dari karya yang, menurut pengakuannya sendiri, berisi proposisi yang pada akhirnya “tidak masuk akal”? Bagi Wittgenstein, nilai dari Tractatus terletak dalam proses pemikiran yang dia undang pembacanya untuk ikuti, bukan dalam kesimpulan konkret yang dihasilkannya. Filsafat Wittgenstein bertujuan untuk menunjukkan bahwa pemahaman sejati sering kali terletak dalam mengenali batasan-batasan kemampuan kita untuk berbicara dan berpikir dengan jelas tentang dunia, daripada dalam jawaban-jawaban definitif yang mungkin kita cari.
Tractatus tidak hanya menjadi teks yang mengajarkan tentang logika dan bahasa, tapi juga tentang bagaimana berfilsafat—yaitu, bagaimana mengenali batasan-batasan pengetahuan kita dan bagaimana kita harus berpikir tentang pertanyaan-pertanyaan yang tampaknya tidak dapat dijawab.
Wittgenstein “Akhir”
Transisi Ludwig Wittgenstein dari pendekatannya yang awal ke yang akhir adalah sebuah pergeseran intelektual yang dramatis, dipicu oleh introspeksi diri dan kritik terhadap asumsi-asumsi sendiri. Setelah menerbitkan Tractatus Logico-Philosophicus, Wittgenstein mulai merasa bahwa fokusnya yang terlalu sempit pada aspek-aspek logis dan benar-salah dalam bahasa telah mengabaikan fungsi dan aspek lain yang sama pentingnya dalam penggunaan bahasa sehari-hari. Dalam Tractatus, dia terutama membahas proposisi-proposisi yang memiliki nilai kebenaran yang jelas, seperti “besok adalah Senin” atau “langit itu hijau”. Namun, ia kemudian menyadari bahwa bahasa juga berfungsi dalam cara yang tidak sesederhana itu, membawanya kepada penyesalan atas “kesalahannya” sebelumnya.
Perubahan pandangan ini tercermin dalam karya selanjutnya, Investigasi Filsafat, di mana Wittgenstein menjelajahi bagaimana makna sebenarnya terbentuk dalam penggunaan sehari-hari dan konteks sosialnya. Wittgenstein mengusulkan bahwa bahasa adalah alat yang jauh lebih kompleks dan serbaguna daripada sekedar medium untuk menggambarkan atau mewakili realitas secara langsung. Dalam Investigasi Filsafat, dia memperkenalkan ide bahwa makna bukan hanya tergantung pada representasi objektif, tetapi muncul melalui ‘permainan bahasa’, yaitu aktivitas kolektif manusia yang menentukan bagaimana kata-kata digunakan dalam berbagai konteks praktis.
Wittgenstein menggunakan analogi “permainan” untuk menunjukkan bagaimana bahasa beroperasi dalam berbagai konteks: perintah, lelucon, teka-teki, percakapan biasa, dan banyak lagi, semuanya memerlukan aturan-aturan yang berbeda dan berfungsi dalam cara yang berbeda. Misalnya, ketika seseorang berteriak “Air!”, arti dari teriakan tersebut bisa berbeda-beda: mungkin merupakan perintah untuk membawa air, sebuah komentar sederhana pada cuaca hujan, atau sinyal darurat. Makna kata atau kalimat tersebut bergantung pada situasi sosial dan fungsi linguistiknya pada saat itu.
Dalam pendekatan terakhirnya, Wittgenstein bergerak jauh dari pandangan awalnya yang logisentris dan mengarah ke pemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang bahasa. Dia mengajarkan bahwa untuk memahami makna kata-kata dan ekspresi, kita harus melihat bagaimana mereka digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dan bagaimana mereka terintegrasi dalam aktivitas sosial manusia. Ini membawa pemikiran filsafat ke wilayah yang lebih praktis dan terkait erat dengan kehidupan manusia, menjauhkan dari teori abstrak yang mendominasi fase awal kariernya.
Pandangan Ludwig Wittgenstein tentang Peran Filsafat
Konsep “permainan” yang digunakan Ludwig Wittgenstein dalam mendiskusikan bahasa menggambarkan betapa kompleks dan bervariasinya cara kita menggunakan kata-kata dan bahasa. Sebagaimana permainan yang sulit untuk didefinisikan secara tegas dan unik—tidak semua permainan memiliki aturan yang tetap, tidak semua dimainkan oleh lebih dari satu orang, dan tidak semua memiliki tujuan untuk menang—demikian pula dengan bahasa. Wittgenstein menunjukkan bahwa tak satu pun definisi yang bisa secara sempurna merangkum semua bentuk atau fungsi bahasa. Alih-alih, apa yang bisa kita lakukan adalah menjelajahi dan menganalisis bagaimana bahasa digunakan dalam konteks praktis yang berbeda.

Dalam pandangan Wittgenstein Akhir, banyak permasalahan dan pertanyaan filsafat muncul dari salah pemahaman atau salah penggunaan bahasa. Misalnya, ketika filsuf bertanya, “Apa itu pengetahuan?”, mereka mungkin tak menyadari bahwa mereka mengambil kata dari konteks penggunaan sehari-harinya dan memberikannya makna baru atau paksaan yang tidak cocok dengan penggunaannya yang lebih organik dan alami. Menurut Wittgenstein, kata “pengetahuan” dan maknanya seharusnya dipahami berdasarkan bagaimana kata tersebut biasanya digunakan dalam bahasa, bukan dalam penggunaan filosofis yang sering kali memaksa dan membingungkan.
Oleh karena itu, tujuan utama filsafat, menurut Wittgenstein, harusnya adalah untuk “menjernihkan” kebingungan yang timbul dari penggunaan bahasa ini. Filsafat harus membantu kita memahami dan memperjelas bagaimana kata-kata digunakan dalam kehidupan sehari-hari, bukan memutarbalikkan makna mereka untuk memenuhi agenda teoretis yang abstrak. Dengan demikian, filsafat sejati bertujuan untuk menerangi dan menghilangkan kebingungan, memfokuskan pada analisis praktis dari penggunaan bahasa untuk mengurangi kesalahpahaman dan kesalahan interpretasi yang tidak perlu.
Melalui pendekatan ini, Wittgenstein mengajak kita untuk melihat bahasa dan filsafat tidak sebagai pencarian abstrak untuk kebenaran yang universal, tetapi sebagai usaha praktis untuk memahami dan memperbaiki cara kita berkomunikasi dan berpikir tentang dunia sekitar kita.















